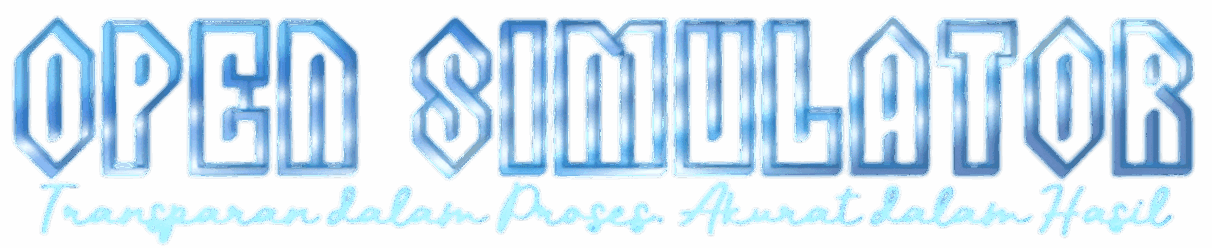Potret Ketahanan Keluarga Kecil di Jakarta di Balik Gang Sempit Jakarta Selatan
Di tengah gegap gempita ibu kota yang tak pernah tidur, masih ada kisah tentang Ketahanan Keluarga Kecil di Jakarta dan perjuangan hidup yang jarang tersorot kamera. Salah satunya adalah kisah Mawi, seorang pria paruh baya yang tinggal di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Bersama istri dan dua anaknya, Mawi menyewa rumah petak sederhana dengan penghasilan bulanan hanya Rp 700.000 sebagai penjaga kebun.
Dalam kondisi tersebut, keluarga ini harus bertahan dengan alokasi belanja harian kurang dari Rp 20.000 per orang. Meskipun jumlah tersebut bahkan di bawah garis kemiskinan nasional, mereka tetap berjuang untuk hidup, bukan sekadar bertahan.
Menelisik Garis Kemiskinan Nasional: Hidup di Bawah Standar Layak
Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan nasional saat ini berada pada angka Rp 609.160 per kapita per bulan, atau setara dengan Rp 20.305 per hari. Keluarga Mawi hidup sedikit di bawah batas ini, namun tetap berada dalam zona merah kategori miskin.
- Di kota, angka garis kemiskinan naik menjadi Rp 629.561 per bulan.
- Di desa, juga mengalami kenaikan menjadi Rp 580.025.
- Kontribusi terbesar berasal dari makanan, dengan proporsi mencapai 74,58%, sementara 25,42% sisanya dari nonmakanan seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan.
Keseharian Penuh Perhitungan: Mengelola Hidup dengan Rp 500.000 Sebulan
Dalam wawancara dengan Kompas.com, Mawi menyebutkan bahwa pengeluarannya untuk makan bisa ditekan hingga di bawah Rp 500.000 per bulan. Ia memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan primer seperti makan dan listrik, dengan penghematan ketat pada kebutuhan sekunder lainnya.
Strategi Bertahan Hidup Mawi:
- Memasak sendiri untuk menghindari jajan di luar.
- Belanja di pasar tradisional untuk harga yang lebih murah.
- Menekan konsumsi listrik dan air seminimal mungkin.
- Menghindari cicilan dan utang, agar penghasilan tidak habis untuk bunga.
Suara dari Warga Lain: “Bisa, Tapi Tak Layak”
Romys, seorang pekerja swasta berusia 30 tahun yang tinggal di Jakarta, mengakui bahwa secara teori memang memungkinkan untuk hidup dengan Rp 600.000 per bulan, namun sangat jauh dari kata layak. Ia menekankan bahwa bertahan hidup bukan berarti benar-benar hidup.
“Bisa sih, asal cuma makan dan tidur. Tapi ya hidup seperti itu bukan kehidupan yang layak, apalagi di Jakarta,” ucapnya.
Romys menyoroti fenomena sosial yang sering luput dari perhatian: banyak warga ibu kota yang secara diam-diam hidup dalam tekanan ekonomi luar biasa. Mereka mengandalkan berbagai strategi bertahan hidup, dari bekerja serabutan, mengamen, hingga mengandalkan bantuan sosial.
Garis Kemiskinan: Ukuran Ekonomi atau Realitas Sosial?
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menegaskan kembali bahwa garis kemiskinan bukan sekadar angka, melainkan alat ukur yang merepresentasikan kemampuan ekonomi seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar.
“Garis kemiskinan adalah batas pengeluaran minimum yang digunakan untuk mengklasifikasikan seseorang sebagai miskin,” ujarnya.
Kenaikan angka garis kemiskinan ini mencerminkan meningkatnya biaya hidup, terutama di sektor pangan. Namun, bagi mereka yang hidup jauh di bawah angka tersebut, seperti Mawi, kenaikan ini justru menjadi cermin dari makin lebarnya kesenjangan sosial.
Menilik Lebih Dalam: Ketimpangan Ekonomi di Perkotaan
Fenomena yang dialami Mawi bukanlah kasus tunggal. Di berbagai sudut Jakarta, terdapat ribuan keluarga yang menghadapi dilema serupa: tinggal di kota besar dengan penghasilan yang bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Realitas yang Mengkhawatirkan:
- Bantuan sosial terbatas dan tidak merata distribusinya.
- Kenaikan harga bahan pokok tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan masyarakat kelas bawah.
- Biaya tempat tinggal dan listrik di Jakarta terus melambung.
Transisi dan Refleksi: Saatnya Melihat Lebih Dalam
Cerita Mawi dan ribuan warga lain menyuguhkan sebuah pertanyaan besar: apakah cukup bagi pemerintah untuk sekadar menentukan garis kemiskinan tanpa mengubah struktur pendukungnya? Tanpa kebijakan konkret yang mengatasi akar masalah, maka angka-angka hanya menjadi statistik, bukan solusi.
Ketangguhan dalam Sunyi
Meski hidup dalam keterbatasan ekstrem, Mawi dan keluarganya tidak menyerah. Di tengah kerasnya ibu kota, mereka tetap menunjukkan bahwa semangat bertahan hidup tak mengenal angka. Namun, seberapa lama ketangguhan ini bisa bertahan tanpa dukungan nyata dari sistem sosial dan ekonomi yang lebih adil?